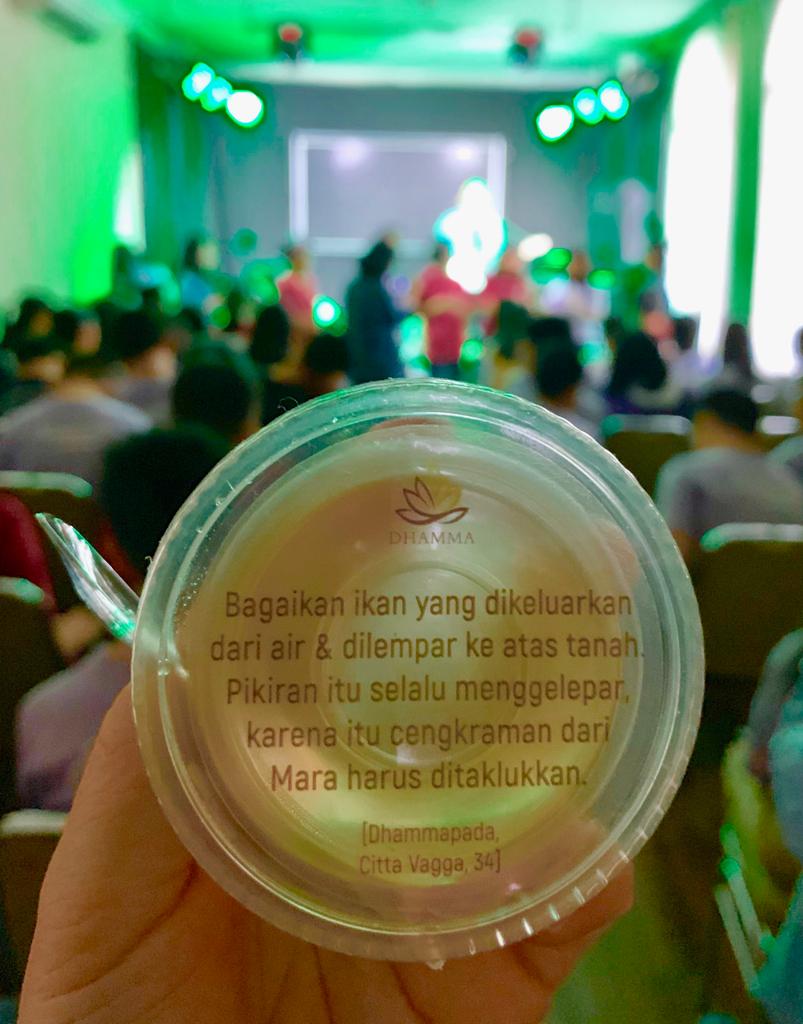Lima


NARASI berita kasus di atas terdengar sayup-sayup dari televisi. Si empunya (Warman Nasution) menghampiri. Ditontonnya sejenak, sebelum kemudian dia matikan layarnya sambil agak bersungut-sungut. Kepada Adi (Baskara Mahendra), dia mengeluh makin langkanya kemanusiaan ditemui di masyarakat.
Inilah bagian pembuka tentang sila ke-2 Pancasila dalam “Lima”, film Lola Amaria Productions yang dirilis 31 Mei lalu. Tentu saja bercerita tentang “kemanusiaan”, diarahkan pada konteks tindakan yang adil dan beradab. Meski ada spektakel yang menggantung di pengujung konfliknya.

Cukup dengan melihat posternya saja, kita akan tahu bahwa Pancasila dijadikan landasan keseluruhan plot. Semua dijahit sedemikian rupa bukan sebagai omnibus, dan disajikan sesuai urutan sila. Rangkaian ceritanya adalah pilinan atas “Ketuhanan”, “Kemanusiaan”, “Persatuan”, “Musyawarah”, dan “Keadilan”.
Ditangani lima sutradara berbeda, setiap bagian tentu menyuguhkan nuansa yang tidak sama. Dari sisi cerita, dialog dan objek teknis lain, serta hasil akhirnya, ada fragmen yang begitu mudah membuat penonton bergumam. Ada pula yang meninggalkan kesan berkebalikan, dan menyisakan tantangan besar untuk proses penyuntingannya.
Kendati demikian, fragmen-fragmen yang dimaksud tersebut setidaknya tetap cocok dijadikan materi pengaya PMP/PPKn/PKN maupun diskusi-diskusi filsafat etis. Hanya saja, “Lima” dirating Dewasa 17+ oleh Lembaga Sensor Film (LSF); tak mungkin ditayangkan di hadapan pelajar.
Bagi saya, bagian terkuat ada di cerita pembuka, tentang sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Entah, barangkali lantaran agama merupakan isu yang sangat sensitif, menjadikan fragmen ini cukup lentur untuk didramatisasi. Apalagi didukung oleh sinematografi yang tak kalah dramatis juga. Salah satunya ketika Aryo (Yoga Pratama) yang seorang Kristen, turun ke liang lahat ibunya (Tri Yudiman) yang seorang muslim balikan. Dibarengi line yang–sebenarnya cukup lazim kita dengar sehari-hari, tetapi dalam film ini–terasa menghentak.
“Biar dosanya kami yang tanggung.”
https://www.instagram.com/p/BjM9iDRDnBJ/?hl=en&taken-by=lola.amaria
Wajar bila ada sebagian penonton yang merasa terganggu dengan kisah ini. Mulai dari sekadar mengernyitkan dahi, mempertanyakan penggambaran, sampai yang tersinggung. Menganggapnya terlalu mengada-ada, memojokkan, dan tidak sesuai dengan keadaan riil di masyarakat.
Saya yang bukan seorang muslim pun sempat membatin: “Apa iya bisa sampai sebegitunya?” Hingga teringat sesuatu, dan menimpalinya sendiri: “Oh, di Jakarta sih kelihatannya pernah begitu.”
Alih-alih berbicara tentang ketakwaan dan keimanan personal (ketuhanan punya banyak aspek, kan?), bagian pertama dari “Lima” ingin menunjukkan tentang kerukunan, sikap saling menghormati dan menghargai, serta keluwesan sosial terhadap penganut agama berbeda. Tak terhindarkan, efek samping yang dapat muncul pada para penonton adalah terlintasnya pemikiran-pemikiran berikut:
- “Makanya, cari pasangan yang seagama.”
- “Makanya, anak-anak diajarkan agama yang sama, dan jangan sampai pindah.”
- “Makanya, jangan pindah agama.”
Kembali dikaitkan dengan PMP/PPKn/PKN, fragmen ini berimplikasi pada bagaimana kita sepatutnya menyikapi situasi ini? Apakah menuding, memaklumkan, atau tidak diacuhkan saja? Pastinya, fragmen ini memancing diskusi dan pembahasan lebih lanjut. Bukan semata-mata sebagai umat agama tertentu, melainkan sesama warga negara.
Bergulir ke konflik kedua, yang terfokus pada aksi main hakim sendiri dan kepatuhan pada hukum formal. Sayangnya, belum sampai menyentuh titik paling krusial, dan hanya menyampaikan ulang bahwa kekerasan massal yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah brutalisme. Sudah diiyakan dan diketahui hampir semua orang di negara ini, akan tetapi belum tentu bisa mereka laksanakan.
Akan sangat menarik apabila adegan persidangan ala Conviction la Raisonee (?) yang ada di fragmen terakhir, sila ke-5, dimunculkan ke dalam fragmen kedua. Lengkap dengan sang jaksa (Sapto Soetardjo) yang sukses bikin sebal lewat aktingnya. Antiklimaks bagian kedua pasti tak sesederhana yang ada. Sebab sama saja, siapa yang tidak penasaran apa alasan yang mendorong Pak RT di atas melakukan perbuatannya.
Khusus segmen ketiga, tema “Persatuan” dipadukan dengan masalah integritas. Fokus yang diangkat ialah urusan ras dan keangkuhan etnis. Peristiwa Mei 1998 pun turut disertakan. Dalam hal ini, lebih gereget jika Tony (Willem Bevers) menggunakan kata “Cina” daripada “Tionghoa”. Mengeskalasi tensi cerita.
Segmen keempat menempatkan Adi sebagai figur yang tidak konsisten. Di bagian kedua, dia menjadi seseorang yang berani, sanggup menghadapi ketakutannya sendiri, bertanggung jawab, dan bertindak benar. Sedangkan di bagian keempat, dia benar-benar seorang adik bungsu dalam pusaran drama keluarga. Adi terlihat belum dewasa, dan jatuh dalam asumsi dangkal mengenai masa depannya. Sementara kakak-kakaknya, Fara (Prisia Nasution) dan Aryo, juga tengah berjibaku dengan masalah hidup masing-masing.
Di segmen terakhir, ada sudut pandang yang kontradiktif, dan sukar untuk tak diasosiasikan dengan fragmen kedua karena kesamaan komponen cerita. Sama-sama menampilkan maling kecil yang mencuri benda remeh, tapi beda nasibnya. Hal ini tak terlepas dari pemaknaan atas “Keadilan” atau pun “Keadilan Sosial”.
Semua individu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Pencurian, sekecil apa pun, tetaplah merupakan upaya seseorang mengambil barang yang bukan haknya. Yang membedakan adalah barang yang diambil; nilainya; dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan dari pencurian tersebut. Kesemuanya memberi bobot yang memengaruhi pertimbangan hakim saat menjatuhkan vonis.
Dalam fragmen ke-5, Agus (Aji Santosa) gagal menjelaskan alasannya mencuri buah kakao. Sang jaksa memiliki poin valid bahwa pencurian tetaplah pencurian, meskipun hanya sedikit, dan itu pun telah dikembalikan. Bakal lebih melegakan dan membesarkan hati penonton, jikalau bunyi putusan hakim tetap diperdengarkan. Baik dibebaskan murni, atau hanya disanksi denda ganti rugi.
Bagaimanapun juga, perangkat hukum berperan penting dalam tercapainya keadilan dan keadilan sosial. Untuk itu, sikap arif dan bijaksana mutlak dimiliki oleh mereka yang berwenang.
Lantas bagi Agus, apa pun vonis yang dijatuhkan hakim, dia harus tetap sadar atas tanggung jawabnya. Yaitu bersikap adil kepada dirinya sendiri; memahami dan mengakui apa yang dia perbuat, serta bersedia menjalani konsekuensinya. Adil secara menyeluruh. Bukan hanya menerima dan menikmati keadilan, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkannya. Seperti yang dilakukan Adi dan dialami Dega Pratama (Ravil Prasetya) di bagian kedua.
Mencoba menyuguhkan realitas kehidupan sosial yang kita temui sehari-hari, yang beberapa di antaranya dikorek dari sisi terdalam dan kerap kita hindari, “Lima” adalah film yang pasti berujung pada diskusi. Boleh dibilang merupakan ilustrasi banal dan cukup dark bagi kajian PMP/PPKn/PKN yang masih diajarkan di sekolah sampai saat ini.
Durasinya cukup panjang (lebih dari dua jam), dan tentunya bukan pekerjaan mudah untuk mengakomodasi semua ide maupun pesan yang ingin disampaikan. Namun, dengan total salinan digital yang tak lebih dari 32 unit, bukan mustahil film ini bisa segera hilang dari peredaran. Mumpung masih tayang, silakan disaksikan.
[]