Jadi Orang Cina di Indonesia

TULISAN ini boleh dibilang eksposisi atau uraian dari serangkaian twit Jumat (2/3) sore, kemarin. Ditulis kembali di sini agar tercatat lebih rapi, lebih komprehensif dan diupayakan minim bias, serta memudahkan diskusi selanjutnya. Sebab topik yang dibahas—seperti yang tergambarkan dari judulnya—menjadi bagian dari kenangan sekelompok orang berdarah Cina … atau sebut saja Tionghoa Indonesia.
Kenangan yang kurang menyenangkan.
Sayangnya.
bikin versi blognya mungkin, biar bs share di fb. tantangan jg nih buat aku seorang ibu tuk ngajarin anak berbeda itu biasa. apalagi tinggal di pinggiran gitu.
— Amaliya R R (@amelluv) March 2, 2018
Sejujurnya, tidak ada rencana sama sekali untuk menulis twit tentang hal ini. Sampai akhirnya tanpa sengaja ketemu dan membaca salah satu twit warganet yang berisi sentimen negatif terhadap eksistensi warga Tionghoa di Indonesia.
Berawal dari sini.

Membaca twit di atas, muncul pertanyaan: “Benarkah orang Tionghoa Indonesia tidak punya jati diri?” Lalu: “Seperti apakah orang Tionghoa yang ada di akar rumput? Apakah orang Tionghoa yang miskin, atau orang Tionghoa yang tercerabut dari akar budayanya sendiri?”
Tampaknya hanya si pemilik twit, atau para sosiolog dan antropolog budaya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, serta memastikan kedudukan warga Tionghoa di Indonesia. Apakah sama dan setara seperti warga etnis lain, atau masuk kategori kelas dua.
Sebelum ini, ada twit pembukanya. Namun, tak ada poin yang penting untuk dibahas. Sekadar pernyataan bullying atau perisakan. Membuat saya terdorong untuk ikut berbagi pendapat dan cerita, bahwa perisakan yang dilakukan secara berkesinambungan tersebut bukanlah soal sikap hidup yang patut dan tidak patut dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini saja, melainkan dipicu oleh kekeliruan dan stereotip masa lalu yang terus-menerus diturunkan.
>> Sebagai seorang Tionghoa di Indonesia, saya sudah terbiasa menjadi korban perisakan atau berada dalam situasi yang demikian sejak kecil.
Pada awalnya, saya tentu kaget; mengapa kondisi itu bisa terjadi? Kemudian menyadari bahwa penyebabnya adalah “Cina, kamu!” Lama kelamaan, mengantarkan saya pada pemikiran: “Oh, mereka mungkin memang begitu…” Pandangan yang memaklumkan tindakan-tindakan tersebut, dan mencoba untuk terus mencari akar penyebabnya.
Salah satu dugaan saya, kemungkinan besar mereka (sebaya maupun lebih tua) tidak sadar sedang melakukan perisakan. Apa pun alasannya, mereka barangkali menganggap tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar, menjadi kebiasaan, lalu diteruskan dan dicontoh oleh anak-anak mereka … dan kemudian mengulangi perisakan yang sama, di era berbeda.
Merasa pernah bertetangga atau memiliki teman sekolah yang seorang Tionghoa, tetapi tidak sadar bahwa tindakan yang pernah ia lakukan dulunya adalah perisakan. Kemudian setelah jadi orang dewasa, bisa berucap: “Saya juga punya teman/tetangga Cina, kok… Saya tahu bagaimana harusnya bersikap kepada mereka…”
Sering mendengar ungkapan seperti ini, kan?
>> Di sisi, warga Tionghoa Indonesia yang mengalami perisakan sejak kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dapat merasakan ketidaknyamanan. Memunculkan kenangan buruk, anggapan negatif, dan memengaruhi tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Misalnya, menjadi bersikap kurang akrab dan tidak bisa membaur dengan warga non-Tionghoa, cenderung memasukkan anak-anaknya ke sekolah swasta, lebih memilih lingkungan tempat tinggal tertentu yang mayoritas dihuni sesama warga Tionghoa, dan sebagainya.
Dari sini bisa dilihat, perisakan dan respons negatif yang muncul menimbulkan lingkaran setan.
Warga Tionghoa dirisak sejak kecil, merasa sangat terganggu dan mengalami trauma, membuat mereka berusaha membatasi diri, dan akhirnya terkesan bersikap ekslusif. Lantaran bersikap seperti itu, warga Tionghoa pun kembali menjadi sasaran perisakan. Disebut kurang Indonesia, jaga gengsi, enggan berbaur serta hanya mau bergaul dengan sesamanya, paranoid terhadap orang dari suku lain, dan seterusnya.
Tidak ketinggalan, para orang tua Tionghoa pun akan meneruskan cerita ini kepada anak-anak mereka. Membagi pengalaman tidak menyenangkan dengan maksud agar putra-putri mereka bisa berhati-hati dan menjaga diri.
Di sisi seberangnya, anak-anak non-Tionghoa pun dibesarkan dengan stigma. Mendorong mereka untuk mengejek, mengusik, dan merisak Tionghoa yang ditemui.
>> Tanpa ada simpati, stereotip dan stigma terhadap orang Tionghoa di Indonesia dibiarkan begitu saja dan sesekali mendapat perhatian ala kadarnya.
Ketika ada warga Tionghoa yang terkesan ekslusif dan kurang berbaur secara sosial, langsung divonis tidak mampu bermasyarakat di bumi Indonesia ini tanpa melihat apa penyebabnya, apalagi bersusah payah untuk berkomunikasi dan berkonsolidasi. Membangun diskusi yang bebas dari prasangka dan ketegangan sosial.
Sejak kecil, saya jauh lebih sering mendengar imbauan kepada warga Tionghoa untuk lebih bisa berbaur, mengakrabkan diri dengan anggota masyarakat lain, dan kalimat-kalimat sejenisnya. Hanya saja, amaran tersebut disampaikan dengan alpa melihat apa yang menjadi akar di balik sikap sebagian warga Tionghoa tersebut.
Mengambil contoh twit di atas tadi, masih ada orang usia dewasa yang bisa merisak dengan berucap “Orang Cina tidak diterima di kampung halaman, lalu teriak ‘aku Indonesia’ biar punya jati diri!”
Serbasalah, ya. Saat orang Tionghoa mengucap “aku Indonesia” justru dianggap karena tidak punya jati diri. Akan tetapi saat tidak mengucap apa-apa, malah dianggap pasif, kurang nasional, dan dipertanyakan kesetiaannya terhadap Tanah Air ini. Karepé opo toh, Mas?
Saya berharap, hanya si pemilik twit itu saja yang bisa berpikiran demikian. Jangan sampai twit ini mengindikasikan adanya fenomena gunung es atas sikap antipati dan diskriminasi terhadap warga Tionghoa di Indonesia.
>> Mengenai perisakan ini pun, warga Tionghoa Indonesia sejauh pengamatan saya, memiliki dua jenis respons berbeda.
Ketika bocah Tionghoa dirisak, ada yang:
- Akhirnya cenderung bersikap defensif. Menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan dibanding si pelaku, dan kemudian melakukan penghindaran secara sosial. Sikap ini bisa mendorong bocah Tionghoa tersebut menjadi seseorang yang eksklusif. Ditandai juga dengan ungkapan: “Sudahlah, kita Cina, kita mengalah saja.” Mengalah di sini termasuk menarik diri.
- Ada yang merasa marah, sangat tidak terima, sampai-sampai malah menjadi benci dengan ketionghoaannya. Merasa tidak nyaman dengan identitas budaya tersebut, dan bahkan berusaha untuk menanggalkannya.
Seperti cerita Ernest Prakasa dalam film “Ngenest”, atau penuturan Lola Devung, seorang teman dari Samarinda, dalam artikelnya: “Imlek dan Saya, It’s Who I Am”
Berikut petikannya.
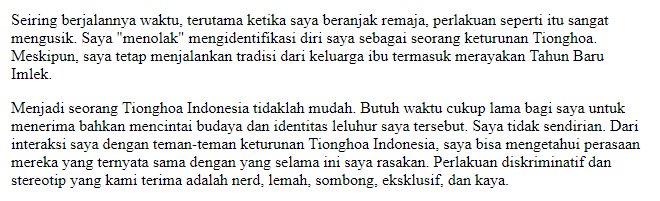
Contoh lain.
Gw ga nyaman sama kecinaan ini sampe sekarang. People who know me close enough must heard me always say "gw indo lah, bungkusnya doang kejebak cina" https://t.co/z7BL7oWMOL
— anakmecin (@anakmecin) March 2, 2018
>> Tak bisa dimungkiri, lingkungan keluarga dan keseharian sangat berpengaruh. Kehidupan bermasyarakat di kota kecil jauh berbeda dibanding kota.
Saya dan keluarga boleh dibilang beruntung, tinggal di lingkungan yang relatif ramah. Kami cuma satu dari sedikit keluarga Tionghoa di kecamatan lingkar luar Samarinda. Ramahnya tetangga pun bukan karena basa basi sosial ala pelajaran PMP/PPKn.
Faktor-faktor itu bisa jadi yang menyebabkan saya dapat berpikiran seperti sekarang. Melihat perisak dan perisakan sebagai sebuah akibat, saling bertumpukan dengan sebab. Apabila saya seperti Tionghoa kebanyakan, akan tidak acuh dengan urusan ini.
Karena ini pula, saya menjadi yakin bahwa jargon-jargon pembangunan sosial macam: “Mari kita jaga dan tingkatkan kerukunan, dan sikap menghormati dalam masyarakat” akan tetap jadi tidak berguna selama indoktrinasi rasial tetap dilakukan di rumah.
Hormatilah orang lain, sebagaimana kamu ingin orang lain menghormatimu.
Masalahnya, siapa yang bersedia memulai menghormati terlebih dahulu? Semuanya cenderung mau mendapatkan, baru setelahnya memberikan. Apa penyebabnya? Ya lingkaran setan tadi.
Yang satu merasa tidak perlu repot-repot menghormati dan menghargai, yang satunya lagi merasa sudah jadi korban selama ini dan telah berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi sumber masalah. Buat apa berdekat-dekatan lagi?
Kecuali kalau untuk tujuan bisnis.
Dianggapnya semua Tionghoa begitu, kan? Mementingkan usaha saja.
>> Dengan sikap egois seperti ini, pantas saja waktu pindah dari Samarinda ke Jakarta sempat kaget saat ketemu segelintir warga Tionghoa yang cueknya minta ampun.
Mereka mungkin terbiasa untuk tidak dekat-dekat dengan warga non-Tionghoa. Sikap yang tidak terbiasa bergaul dengan orang lain itu, membuat mereka terkesan cuek dan tidak peduli sosial.
>> Satu kasus.
Waktu itu sedang naik ojek online, lewat jalan tikus di sekitar Angke.
Bapak ojeknya aktif tanya-tanya warga sekitar supaya tidak tersasar. Sampai satu kali ada engkoh-engkoh berdiri depan pintu rumah. Begitu ditanya, eh dia malah buang muka, melengos begitu saja. Tidak dihiraukan.
Saya jelas kesal lah…
>> Waktu dia tidak jawab, saya langsung spontan bicara: “不會講話的嗎?” (tidak bisa ngomong, ya?)
Eh, dia kayaknya agak kaget. Mungkin karena saya berkulit gelap sehingga dikira bukan Tionghoa. 😅 Serupa tetapi tak sama dengan kasusnya Mbak @cho_ro soal tempat duduk di bus.
Kronologinya gini, wa lagi di TJ dan sebelah wa kosong, trus wa colek buibuk itu buat duduk sebelah wa. Dia ga mau dan bilang, "saya muslim"
YA TRUS EMANG WA BABIK APA GIMANA 😭😭😭
Wa jawab, "eh, saya muslim bu." dia cuma ketawa sambil bilang "oh saya kira Kristen".
WHAAAAAT.
— | chor0 (@cho_ro) February 4, 2018
>> Bedanya, kasus Mbak Choro soal tampilan dan agama, sedangkan kasus saya soal tampilan rasial saja.
Itu sebabnya, saya percaya urusan toleransi dan kerukunan begini bukan cuma masalah hilir (apa yang terjadi di sini, saat ini). Karena apa yang dilakukan anak-anak zaman sekarang, pasti berasal dan mengakar dari para pendahulunya.
>> Penting banget untuk saling bertukar posisi dan sudut pandang. Supaya bisa menghilangkan asumsi dan rasa tidak nyaman yang tak beralasan.
Rasa tidak nyaman yang tak beralasan itu contohnya:
“Aku enggak suka sama kamu.“
“Kenapa?“
“Karena kamu Cina.“
Tak beralasan, kan?
>> Iya! Ini memang merupakan masalah sosiologi, psikologi, dan etika sosial. Bukan sekadar hukum.
Cuma, bakal repot kalau ternyata banyak sosiolog, psikolog, dan pakar etika sosial yang juga berpandangan rasial. Quick fix yang dilakukan pun hanya formalitas. Macam keputusan voting rapat kelurahan. Iya-iya doang.
… dan ini terjadi di kedua sisi. Jangan lupa, pernah ada masanya ketika almarhum Kristoforus Sindhunata (王宗海) dengan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) menyodorkan terapi ekstrem untuk meminimalisasi pertikaian rasial di Indonesia: yaitu pembauran secara total dengan penghilangan identitas ketionghoaan dan pernikahan campur.
Lah, iya kalau kedua orang Tionghoa dan non-Tionghoa bersedia menikah. Jika salah satunya saja, bukankah itu pemaksaan?
>> Nah, berbicara soal pernikahan campur, justru bertolak belakang dengan nuansa yang terjadi dalam perisakan terhadap warga Tionghoa.
Kontradiktif dengan tindakan diskriminatif dan perisakan tadi, malah muncul gejala kebanggaan berlebih ketika ada non-Tionghoa konservatif yang akhirnya “berhasil” menikah dengan warga Tionghoa Indonesia. Laiknya sebuah kesuksesan luar biasa, ketika pernikahan campur (amalgamasi) itu terjadi.
Ini benar banget, semacam penaklukan. Bahkan di kampung saya ketika akhirnya menikah dgn tionghoa, mendadak merasa tionghoa, statusnya langsung naik dan lupa asal, ini berdasarkan apa yg saya lihat selama ini di kampung saya, di keluarga saya 😊😊
— Aling (@NonAling) March 2, 2018
>> Apalagi kalau pernikahan campur itu dibarengi dengan perubahan agama. Semacam sukses besar. 😅
Maaf kalau pernyataan ini terkesan spekulatif. Mudah-mudahan bakal ada penelitiannya yang merekam sentimen sosial terhadap pernikahan campur Tionghoa dan non-Tionghoa secara valid. Biar ilmiah. Contohnya baru siang tadi.
>> Ada teman kantor yang out-of-nowhere bisa bicara begini.
“Gon, kamu punya kenalan, enggak? Cewek. Chinese, tapi dia Islam…”
“Ha? Hmm… Ada. Di Samarinda…“
“Yah… Kok di Samarinda. Kan mau aku pacarin…”
Akhirnya aku tanya… “Kenapa mesti Cina?”
Senyam-senyum thok…
>> Selain perisakan untuk tujuan menganggu, mengintimidasi, dan membuat perasaan tidak nyaman, tindakan sejenis juga dilakukan pada sektor-sektor kehidupan yang lain kok. Sebagai minoritas, dan agak merasa orang (yang di)asing(kan) di republik ini, warga Tionghoa ya bersikap kooperatif. Nrimo dan akhirnya mengalah untuk mengupayakan hal lain.
Sampai ketika mereka berhasil lewat usahanya sendiri, tetap dianggap sebagai pembawa dampak negatif bagi masyarakat lain.
Ambil contoh pembatasan pemilikan tanah di Yogyakarta atas dasar rasial. Yo ben. Para Tionghoa Indonesia setempat ya akan terus berusaha sejahtera. Beli tanah di tempat lain, kek, atau cukup dengan mengupayakan semampu-mampunya saja. Asal cukup makan, berpenghasilan, dan menabung.
>> Ya jangan kaget.
Waktu masih kecil, bocah-bocah Tionghoa bisa diledek teman sekolahnya sesederhana:
“Dasar Cina, kamu!“
Setelah gede, ejekannya berubah jadi …
“Dia kan Cina, pasti duitnya banyak.”
“Dia kan Cina, pasti bisa menguasai perekonomian di sini.”
“Dia kan Cina, antek Aseng!“
Hmm… Jadi teringat sebuah kejadian, dan mudah-mudahan saya salah ingat.
Rumah orang tua mengalami kebakaran sekitar tahun 2002 atau 2003 silam (secuplik kisahnya bisa dilihat di akun Instagram). Terdampak api yang merembet dari titik asalnya. Aneh, meski sama-sama menjadi korban kebakaran, hanya keluarga saya dan paman (rumah kami bersebelahan) yang tidak mendapatkan bantuan donasi dari pihak kecamatan setempat dan/atau pemerintah kota.
Apabila kami dianggap sebagai keluarga yang berada sebagai alasannya, ya tidak apalah. Anggap saja itu doa.
Kenapa kami sampai akhirnya tahu telah dilewatkan dari pemberian bantuan tanpa penjelasan? Karena para tetangga dekat sesama korban kebakaran yang bercerita. Mereka bahkan bersedia bersama-sama menyisihkan sedikit bantuan keuangan yang diterima, untuk diberikan ke orang tua saya.
Ditolak. Dia tak sampai hati menerimanya.
Sekali lagi, mudah-mudahan ingatan saya ini tidak benar.
>> Dengan perisakan yang dilakukan, tindakan diskriminatif, sentimen negatif, dan lingkaran setan, bukan mustahil warga Tionghoa Indonesia bisa jenuh. Dalam ketidaknyamanannya yang terus terpupuk sejak lama, bisa mengarahkan pada tumbuhnya kebanggaan rasial.
Makin ditekan, makin berupaya untuk bertahan.
Agak menyerempet dengan apa yang terjadi pada warga kulit hitam sedunia saat ini. Mereka merasa begitu terhubung dengan sentimen dari “Black Panther” dan konsep “African/Black Pride”.
Bandingkan dengan Tionghoa Indonesia yang bisa bilang: “Aku WNI, aku cinta Indonesia, dan aku juga bangga terlahir sebagai seorang Cina.”
Pada poin ini, perisakan dan sejarah kelam di masa lalu bisa memunculkan kebanggaan etnik bagi warga Tinghoa Indonesia. Bisa menghasilkan pernyataan: “Apa pun yg terjadi, kami adalah orang Indonesia, dan tetap bangga terlahir sebagai Cina.”
… atau, memilih eksodus. Saking tidak kondusifnya negara ini.
Harap dibedakan, “Cina” atau “Tionghoa di sini bukan sebagai negara, bukan pula sebagai entitas bangsa, melainkan sebagai akar budaya.
Bedanya, sejarah warga kulit hitam diwarnai penyiksaan dan perbudakaan, sedangkan orang Tionghoa mungkin tidak semengerikan itu di masa lalu. Terjadinya pun di skala dalam negeri, sehingga tidak elok bagi Tionghoa di negara lain untuk ikut bersuara.
Semua berawal dari stereotip dan stigma.
>> Salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk perkara stereotip ini adalah social engagement yang sesungguhnya. Ada rasa simpati, pengertian, pemahaman, dan saling menghargai secara proporsional. Hanya saja, pasti susah untuk dicapai.
Saya ingat waktu SMP, menjelang kelulusan. Ada guru yang berkomentar: “Aku dulu waktu masih sekolah, sebenarnya benci sama orang-orang Chinese. Eh, sekarang malah punya murid andalan orang Cina.”
See?
Perubahan sikap dan pandangan bisa terjadi, tentu dengan pendorong yang kuat. Sebab selama saya diajar oleh beliau, tak pernah sedikit pun merasa didiskriminasi atau dirisak. Perlakuan tidak menyenangkan malah saya dapatkan dari guru lain.
>> Seandainya beliau tetap bersikap rasial selama mengajar, penilaian dan sikapnya terhadap saya yang Tionghoa ini pasti juga bias. Sampai akhirnya, entah apa penyebabnya, beliau bisa berkomentar begitu, dan saya asumsikan beliau akhirnya punya sikap berbeda terhadap orang-orang Tionghoa ke depannya.
>> … atau, mengutip twit yang pertama.
Ya ndakpapa, kami di-💩-💩-in. Giliran bilang “aku Indonesia” disebut biar punya jati diri. Giliran eksodus ke negara lain disebut tidak nasionalis. Hahaha… Yo ben.
>> Selain poin-poin di atas, sebenarnya masih banyak komponen-komponen lain yang diperlakukan secara bias, dan tanpa disadari ikut memperkeruh pandangan buruk terhadap warga non-Tionghoa. Seperti sebutan-sebutan rasial dari kedua pihak, penggunaannya yang salah kaprah dan diperparah dengan pemahaman yang keliru, kemalasan untuk mengkonfirmasi, dan tabiat yang suka meledak-ledak.
Yang penting heboh dulu, salah benar belakangan. Ya, kan keliru.
Pada akhirnya, mau apa pun juga, biar orang Tionghoa Indonesia yang memutar otak dan hati dalam menghadapinya.
Meminjam line populer dari film “Dilan 1990” … “Jangan jadi Cina di Indonesia. Berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.”
Wes biyasa...
[]

Terimakasih. Waktu kecil, pernah saya dianggap Cina saat hidup di Amerika, padahal kulit saya sawo matang. Dan saya merasakan perisakan itu. Sikap ini juga muncul di Amrik.
Terima kasih sudah singgah, dan ikut berbagi cerita.
Di mana pun, stereotip dan stigma pasti bikin susah hati.
terima kasih ka, semoga kisah ini bisa dibaca banyak orang dan memberikan sudut pandang berbeda untuk begitu banyak2 rasisme yang banyak tidak disadari telah dilakukan di indonesia. bahkan sbtulnya tidak hanya untuk etnis tionghoa, sukuisme masih kental di indonesia 🙂
tapi mungkin tuhan maha baik, di masa sma , masa paling krusial saya memiliki banyak teman2 tionghoa yang sangat baik. salah satu hal yg paling saya syukuri dalam hidup. 🙂
Duduk sebangku dengan teman baik saya, seorang etnis tionghoa, belajar bersama di toko, berkunjung di saat imlek dan bahagia dapat angpao dari i’i’ 🙂
kalau gak ada mereka mungkin sy gak seperti sekarang.. temen2 baik yg memaksa saya untuk lebih giat belajar.. 😃
Sama-sama. Bikin bersyukur terlahir jadi orang Samarinda, situasinya bikin kita jadi seperti sekarang ini. 😄